Paralaks Teknologi
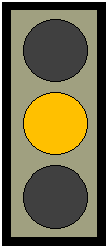 Jumat sore pekan lalu, pulang kerja, dua sepeda motor hampir menabrak saya di perempatan dekat kantor. Ketika itu lampu merah, dan seperti biasa saya ingin buru-buru menyeberang. Eh ada dua motor bablas. Baiknya dengan susah payah keduanya berhasil menghindari saya. Tapi belum putus umpatan mereka, hanya beberapa meter kemudian, keduanya nyaris diseruduk puluhan motor yang mulai bergerak dari arah berlawanan, hendak belok ke kanan. Beruntung, semua berhasil menginjak rem pada saatnya -- ditambah caci maki, tentu saja. Seperti saya, keduanya pun selamat.
Jumat sore pekan lalu, pulang kerja, dua sepeda motor hampir menabrak saya di perempatan dekat kantor. Ketika itu lampu merah, dan seperti biasa saya ingin buru-buru menyeberang. Eh ada dua motor bablas. Baiknya dengan susah payah keduanya berhasil menghindari saya. Tapi belum putus umpatan mereka, hanya beberapa meter kemudian, keduanya nyaris diseruduk puluhan motor yang mulai bergerak dari arah berlawanan, hendak belok ke kanan. Beruntung, semua berhasil menginjak rem pada saatnya -- ditambah caci maki, tentu saja. Seperti saya, keduanya pun selamat.Yang terjadi adalah: kedua motor itu masih sekitar 100 meter dari persimpangan ketika nyala lampu berganti dari hijau ke kuning. Bukannya memperlambat laju, gas malah mereka tancap makin dalam. Sekitar beberapa meter menjelang perempatan lampu berganti merah. Mereka tak bisa lagi menghentikan kendaraannya. Sementara saya, yang hanya berkonsentrasi pada lampu, lansung nyelonong.
Apa hendak dikata, bagi sebagian pengemudi lampu kuning kerap berarti "tancap gas," bukan "bersiap untuk berhenti". Ini bukan hal baru. Barang teknologi memang sering tidak berfungsi/digunakan sebagaimana "harusnya". Mobil misalnya. Konon benda ini diciptakan untuk mempercepat dan mempermudah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Benda ini kemudian disebut alat transportasi. Mobil juga, kemudian, menjadi ektensi dari gengsi dan kenyamanan. Tapi nyatanya, di Jakarta, hampir tidak ada mobil yang tak pernah terjebak macet. Bahkan ada yang sampai berjam-jam. Jam tangan lain lagi. Alat ini digagas untuk membantu pemiliknya mengelola waktu. Toh yang namanya "budaya" molor, tak hilang-hilang juga. Atau, coba perhatikan para anggota DPR RI yang sering bolos rapat meski semua agenda sudah terekam dalam ponsel mereka yang canggih. Contoh lain, trotoar yang dikreasi untuk memberi ruang bagi para pejalan kaki -- kini seolah sengaja disiapkan bagi para pedagang kaki lima. Dan seterusnya. Kalau disebut satu per satu, daftarnya pasti akan sangat panjang.
Kenapa (seolah-olah) ada begitu banyak paradoks dalam penggunaan teknologi?
Dalam dua bukunya: "Future Shock" dan "The Third Wafe" -- yang berbicarakan soal perkembangan kebudayaan yang memuncak pada teknologi -- Alfin Toffler sudah mengisyaratkan hal semacam ini akan terjadi. Alasannya, karena modernisasi atau adopsi teknologi (fisik) berlangsung sangat cepat, sementara adopsi kultur (nilai) berjalan lamban. Ketidaksinkronan ini lalu merangsang terjadinya "kejutan-kejutan" yangdia sebut dengan istilah future shock -- sebagian besarnya adalah kejutan budaya (culture shock).
Teori Toffler masuk akal karena dia, mengevaluasi perkembangan masyarakat dari sudut pandang teknologi: bahwa teknologi menentukan cara hidup masyarakat (technological determinism). Di sini teknologi bukanlah sekedar alat, tapi nilai yang menentukan pembentukan struktur masyarakat. Menurut cara pandang ini, para penyerobot lampu merah, pedagang di trotoar, atau pemilik jam tangan yang masih suka molor adalah orang "sakit" -- menderita simptom personality/cultural disorder. Perbuatan mereka dianggap sebagai penyimpangan yang secara masif bisa menyebabkan kegagalan sosial. Dengan lain kata, cara pandang ini: menggilakan banyak orang!
Tapi tak ada grand theory dalam wacana sosial. Berlawanan dengan pendekatan technological determinism, ada cara pandang lain yang lebih "membebaskan", yakni: social deteminism/social choice). Aliran ini meyakini, masyarkatlah yang menentukan bagaimana memperlakukan sebuah teknologi. Kalau pada aras technological determinism, buruh pabrik bekerja sampai malam karena ada lampu (penerangan), maka menurut pendekatan social choice listrik hanyalah wujud teknologis dari kehendak manusia untuk bisa bekerja lebih lama, termasuk di malam hari. Teknologi, dalam pendekatan ini, bebas nilai. Manusialah yang memberi dia nilai. Makna teknologi secara privat maupun kultural lalu tergantung kepada individu atau masyarakat. Contoh: kalau lampu kuning menandakan sebentar lagi akan merah sementara kalau memacu motor lebih cepat saya yakin bisa melewati perempat sepelum lampu menjadi merah -- kenapa harus memperlambat laju motor saya? Atau, bukan tidak mungkin para anggota Dewan memang sengaja membeli telpon genggam yang mahal agar bisa memasukan semua agenda mereka ke dalamnya, dan dengan demikian bisa menentukan kapan waktunya untuk bolos.
Pendekatan social choice, merelatifkan kesimpulan-kesimpulan yang dibuat dengan cara pandang technological determinism. Yang dianggap menderita personality atau culutural disorder tadi mungkin malah merupakan individu kreatif atau unik.
Persoalannya, saat ini penganut technological determinism tampaknya masih lebih banyak. Seorang teman saya -- termasuk orang kaya di Etiopia -- misalnya, sambil tertawa pernah bercerita tentang beberapa guru miskin dari pelosok di negaranya yang ketika pulang jalan-jalan dari Eropa, atas biaya sebuah NGO, membawa televisi. "Padahal di kampung mereka tidak ada listrik atau pun aki," ujarnya. Dia lupa bahwa di daerah-daerah miskin, memiliki televisi -- dibeli di Eropa lagi -- meski tak bisa berfungsi, adalah sumber esteem bagi pemiliknya.
Yang luar biasa adalah Film "The God Must Be Crazy." Dia menjadi sebuah komedi yang luar biasa -- dan karena itu sangat laris -- hanya karena sebagian besar kita terbiasa berpresepsi dalam aras technological determinism.


0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home